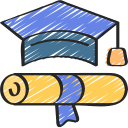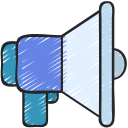Pada akhir Mei 2025 lalu, sayap militer Hamas, brigade Izzuddin Al-Qassam mengeluarkan maklumat bahwa mereka baru saja menghabisi sekelompok Musta’ribin di Rafah Timur. Melalui layar media Al-Jazeera tampak sekitar sembilan orang berseragam sipil dan bersenjata menyisir reruntuhan bangunan lalu mereka memasuki sebuah pekarangan yang sudah dipasang peledak. Bum! Video berdurasi satu menit empat puluh detik itu berakhir dengan rekaman asap hitam.
Musta’ribin atau Mista’arvim dalam bahasa Ibrani, adalah istilah untuk intelijen Zionis yang menyamar dan membaur dengan masyarakat Arab Palestina. Mereka fasih berbahasa Arab, kental berbudaya Arab, mengenakan kafiyeh, dan mengenalkan diri sebagai akamsi alias warga lokal.
Musta’ribin adalah versi pasukan khusus intelijen militer yang terlatih. Tetapi semua taruna militer dan kepolisian di tanah jajahan Israel sejatinya memang diwajibkan bisa berbahasa Arab. Jelas tujuannya adalah untuk memuluskan penjajahan; mengontrol warga Palestina, menjaring informasi, dan menyebarkan propaganda.
Dalam perjalanannya penjajah Israel berhasil memenangkan “perang bahasa” di tahun 1950-an dan sukses menyingkirkan bahasa Arab sebagai bahasa bawaan mayoritas imigran haram Yahudi dari Timur Tengah. Ibrani berkibar, dan Arab mati oleh generasi. Hari ini generasi kedua penjajah tinggal 10% yang berbahasa Arab, dan generasi berikutnya hanya tinggal 1,5% saja.
Meski begitu, sampai tahun 2018 status bahasa Arab masih menjadi bahasa resmi di negara penjajah, setelah Ibrani tentunya. Status itu kini dicabut melalui undang-undang, Arab menjadi bahasa khusus, tetapi bukan lagi resmi. Penduduk Israel Arab yang tinggal sekitar 20% itu umumnya didiskriminasi jika menggunakan bahasa Arab di tempat-tempat kerja.
Secara praktik bahasa Arab memang dipojokkan di Israel, tapi untuk misi penjajahan ia justru dipelajari. Dalam satu dekade terakhir misalnya, minat penduduk Israel belajar bahasa Arab justru meningkat. Inisiatif pembelajaran bahasa Arab bermunculan untuk memenuhi demand-nya. Sekolah bahasa swasta, kelas-kelas di dalam institusi kerja, sampai kursus-kursus di desa-desa jajahan banyak bermunculan.
Misi penjajahan dan kebencian itu terlihat dari proses belajarnya. Salah satu perkuliahan bahasa Arab yang dikutip Al-Jazeera.net dikabarkan melibatkan mantan intelijen militer, aktivis penjajahan, dan diplomat sebagai pengisi kuliah-kuliah pengantar. Mereka mempromosikan fungsi bahasa Arab tidak sekadar bagian dari budaya tapi juga sebagai alat pengendali Palestina.
Dengan alasan yang sama beberapa sekolah menengah di wilayah jajahan Zionis telah menjadikan bahasa Arab sebagai “mata pelajaran wajib”. Pelajar Yahudi diwajibkan melek bahasa Arab.
Tentu terasa janggal bila mendengar bahwa mempelajari bahasa Arab itu “wajib” untuk pelajar Israel. Sementara di waktu yang sama, bangsa apartheid itu justru mendiskriminasi dan menampakkan permusuhan yang membabi buta kepada Al-Qur’an dan para pembacanya, terutama muslim Arab Palestina. Sebegitu nyatanya kebencian itu bisa menjadi bahan bakar untuk belajar.
Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan pelajar muslim di seluruh tanah ‘ajam — non-Arab, termasuk Indonesia, yang tidak menyadari ada hubungan apapun terhadap bahasa Arab?
Bukti Nyata Bahasa Indonesia
Bila boleh menerka, barangkali pelajar muslim tak lagi terdesak belajar bahasa Arab sebab tak sedang ada perlu dengan orang Arab. Atau tak merasa perlu sebab bahasa Indonesia pun mulai dipelajari orang Arab. Atau mungkin alasan lainnya, Al-Qur’an dan tafsirnya pun sudah diterjemahkan, buku-buku, ceramah, dan perkuliahan juga sudah dialih bahasa, kecerdasan artifisial apalagi sudah cukup fasih untuk dipekerjakan. Atau barangkali ada pula keyakinan bahwa Arab hanyalah budaya, sebagaimana Indonesia yang juga kaya akan budaya, maka bahasa Indonesia lebih utama bagi penduduknya dari bahasa lainnya, termasuk Arab.
Khusus yang terakhir ini Indonesia perlu ingat bahwa saat dijajah istilah ‘Bahasa Indonesia’ bukanlah nama bahasa resmi di manapun di wilayah Nusantara. Ia bahasa baru yang diadaptasi dari Melayu. Meski begitu, bahasa itu menjadi tulang punggung gerakan persatuan melawan penjajah sejak peristiwa Sumpah Pemuda. Tanpa satu bahasa tidak ada rasa sama antara Jawa dengan Papua, rasa satu antara Sumatera dengan Maluku. Karena satu bahasa itu maka ide pergerakan cepat tersebar, identitas nasional mulai terbentuk.
Muslim Indonesia seharusnya tidak terlambat menemukan tesis, bahwa begitu pula satu kunci vital melawan penjajah Zionis adalah bahasa persatuan umat: bahasa Arab. Mereka harusnya pertama kali meneriakkan sumpah pemuda internasional di panggung dunia, sebagai putra putri umat, mengaku bertuhan satu, berakidah satu, dan menjunjung bahasa persatuan umat, bahasa Arab.
Shalahuddin Al-Ayyubi, sebagai tokoh pemersatu yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis — dengan berbahasa Arab — adalah orang yang berasal dari suku Kurdi. Begitu pula Nuruddin Zanki, yang berasal dari Turki. Bahkan Izzuddin Al-Qassam yang namanya kini menjadi simbol perlawanan anti-Zionis oleh Hamas adalah tokoh dari Syam dan berdarah Turki. Bila Arab hanya budaya, maka mereka seharusnya lebih fasih berbahasa Kurdi atau Turki. Tapi tidak, bahasa Arab adalah senjata, bahasa pemersatunya.
Antara Wajib dan Lazim
Bila bagi pelajar Zionis belajar bahasa Arab adalah wajib, maka bagi pelajar muslim mempelajarinya adalah bisa lebih dari wajib, yaitu lazim. Bila sesuatu yang wajib artinya adalah jika ditinggalkan bisa berbuah sanksi, maka lebih dari itu, sesuatu yang lazim adalah satu bagian pokok, sebuah kesatuan, yang tidak bisa ditinggal, dan yang tidak bisa terpisahkan.
Ini dijelaskan misalnya oleh Imam As-Syafii (w. 204 H) dalam kitab Ar-Risalah-nya. “Setiap muslim wajib belajar bahasa Arab sejauh kesungguhan yang dia bisa setidaknya untuk memahami syahadat, membaca Al-Qur’an, berdzikir, dan mengucapkan kewajibannya seperti takbir dan Al-Fatihah, dan lainnya.” Ulama lain, semisal Ibnul Hazm (w. 456 H) dalam kitab Al-Ihkam juga mengamini.
Landasan kaidah ushulnya adalah ‘ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib’, dalam kaidah yang serupa bunyinya “sebuah sarana itu hukumnya mengikuti hukum tujuannya”. Jika memahami Al-Quran hukumnya wajib maka sarana untuk memahaminya adalah sama wajibnya. Hal ini yang dijelaskan Ibnu Taymiyah (w. 728 H), dalam karyanya Al-Iqtidha’. Tetapi karena bahkan syahadat itu lazim— yang jika tidak diyakini dan diucapkan maka Islamnya runtuh, maka mengetahui bahasa Arab sebagai bahasanya bisa meningkat pula menjadi lazim.
Tentu ke-lazim-an ini secara syariat hanya mengikat setiap muslim pada tingkat minimal seperti yang dijelaskan Imam Syafi’i. Tetapi pada level pengetahuan bahasa yang mendalam taklifnya adalah bagi pelajar, khususnya pelajar muslim yang mendalami Al-Qur’an dan ilmu syari’at — yang dikenal dengan istilah santri.
Pelajar Muslim yang tidak belajar bahasa Arab itu seperti mobil tanpa roda, pesawat tanpa sayap, atau rumah tanpa dinding, ia keluar dari esensinya sendiri. Tidak hanya salah — tapi ia juga sekaligus runtuh.
Bahasa Arab bagi seorang Muslim adalah bahasa utama sebelum bahasa ibunya sendiri. Sebab Kalam Allah lebih utama dari kalam ibu. Bayangkan, kata yang pertama terdengar saat lahir adalah takbir, saat waktu shalat adalah adzan, saat hendak wafat adalah talqin. Kalimat yang berulang setidaknya tujuh belas kali sehari adalah ayat-ayat Al-Qur’an, dzikir, shalawat, serta doa-doa. Semua kalimat-kalimat yang semestinya dicintai seorang muslim itu berbahasa Arab.
Mengapa lantas Yahudi — yang hanya modal benci —justru yang mewajibkan diri mempelajari bahasa itu, dan bukan orang-orang Muslim yang bermodalkan cinta?
Kalau Zionis bisa melahirkan Musta’ribin, orang Arab buatan, dengan motif permusuhan dan spionase, mengapa pelajar muslim tidak bisa menjadi Musta’ribin, orang Arab tiruan, untuk alasan cinta dan perjuangan?
Atau jangan-jangan cinta itu tak benar-benar tumbuh karena tidak kenal? Sayangnya untuk perkenalan pun harus dimulai dengan belajar.
Maka apapun alasannya tidak ada celah untuk tidak mempelajari bahasa Arab, supaya cinta itu lahir, supaya perjuangan ini tidak berhenti.
Mari ikut berlomba-lomba.
Ditulis oleh Auda Dhiyauddin Zaki, Lc
(Pengajar di Pesantren Hidayatullah Yogyakarta)





.gif)